Sedikit ulasan (sori ngapusi... ternyata gak sedikit hehehe). Tulisan ini berdasarkan dari amatan langsung di kampung dan juga telaah pustaka. Yang paling banyak memberi saya wawasan adalah nukilan buku Thomas Tsu Wee Tan, "Your Chinese Root".
Seorang teman saya di almamater sebuah universitas di Jogja pernah mengeluh, "Jepang itu menjajah kita 3.5 tahun dan meninggalkan luka batin luar biasa. Namun saat ini orang lebih membenci kaum keturunan seperti kami, dibanding dengan kepada orang Jepang." Kata itu ia ungkapkan saat ada acara festival jejepangan di sebuah kampus. Kalau dilihat kasat mata ya kayaknya ya, orang-orang sini begitu kagum sama Jepang dan melupakan penderitaan masa penjajahan mereka yang luar biasa kejamnya. Jadi inget jaman bapak saya ndongeng betapa kejamnya Jepang sama inlander. Tapi luka batin itu begitu cepat terobati. Normalisasi hubungan kedua negara berlangsung lumayan cepat dan mulus.
Cina tak pernah menjajah Indonesia. Namun para perantau dari bangsa ini telah mengukir jejak sejarah yang dalam dan panjang. Tak perlu deh saya daftar satu-satu pengaruh budaya Cina di Indonesia. Saya mau obrolin soal dimensi sosialnya; kenapa warga peranakan (Cina) menjadi minoritas yang punya kekuatan dominan di sektor ekonomi.
Saya merasa gatal untuk nulis gini karena beberapa rekan medsos mulai suka posting bau-bau rasialisme terselubung. Tentu saya tak bisa mengubah mereka. Beberapa orang memang punya "sel" rasialis yang agak dalam untuk dirogoh dan diobati. Di iklim politik yang memanas dan kompleks gini rasanya tetap penting menjaga kewarasan menalar dan menilai. Semoga tulisan ini bisa sedikit membantu.
Seorang teman saya di almamater sebuah universitas di Jogja pernah mengeluh, "Jepang itu menjajah kita 3.5 tahun dan meninggalkan luka batin luar biasa. Namun saat ini orang lebih membenci kaum keturunan seperti kami, dibanding dengan kepada orang Jepang." Kata itu ia ungkapkan saat ada acara festival jejepangan di sebuah kampus. Kalau dilihat kasat mata ya kayaknya ya, orang-orang sini begitu kagum sama Jepang dan melupakan penderitaan masa penjajahan mereka yang luar biasa kejamnya. Jadi inget jaman bapak saya ndongeng betapa kejamnya Jepang sama inlander. Tapi luka batin itu begitu cepat terobati. Normalisasi hubungan kedua negara berlangsung lumayan cepat dan mulus.
Cina tak pernah menjajah Indonesia. Namun para perantau dari bangsa ini telah mengukir jejak sejarah yang dalam dan panjang. Tak perlu deh saya daftar satu-satu pengaruh budaya Cina di Indonesia. Saya mau obrolin soal dimensi sosialnya; kenapa warga peranakan (Cina) menjadi minoritas yang punya kekuatan dominan di sektor ekonomi.
Saya merasa gatal untuk nulis gini karena beberapa rekan medsos mulai suka posting bau-bau rasialisme terselubung. Tentu saya tak bisa mengubah mereka. Beberapa orang memang punya "sel" rasialis yang agak dalam untuk dirogoh dan diobati. Di iklim politik yang memanas dan kompleks gini rasanya tetap penting menjaga kewarasan menalar dan menilai. Semoga tulisan ini bisa sedikit membantu.
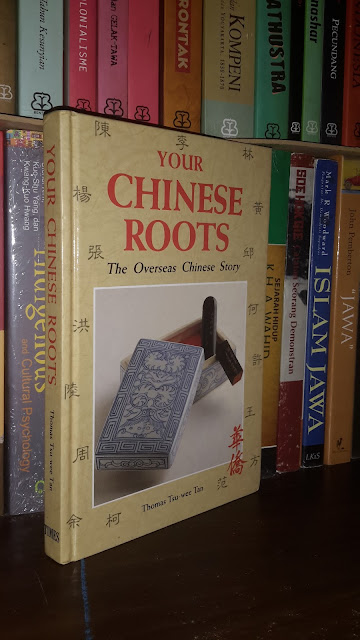 |
| Buku Thomas Tsu Wee Tan, Your Chinese Roots |
SEKILAS SEJARAH
Menurut Dr. Thomas Tsu Wee Tan dalam buku "Your Chinese Roots" perantauan Cina ke seluruh dunia belum terlalu signifikan sampai abad 19. Mereka adalah para pedagang atau pelarian politik. Masa itu para perantau jarang yang menetap. Kalaupun menetap rata-rata berada di pesisir pantai. Cina adalah bangsa perantau yang ulung. Anda tentu tak asing dengan nama besar Admiral Zhenghe (Cheng Ho). Jejak perjalanannya bisa ditemukan di Jawa.
Gelombang imigrasi baru merebak di pertengahan abad 19 saat Dinasti Qing sedang bobrok-bobroknya. Korupsi gila-gilaan para pejabat kerajaan membuat masyarakat tambah miskin. Makin parah lagi ketika Cina jatuh di tangan komunis dan Cina terpecah jadi Republik Rakyat Cina (dengan pemimpinnya Mao Zedong) dan Taiwan (dipimpin Sun Yat Sen). Dari pergolakan dalam negeri inilah, orang-orang terpaksa mencari penghidupan hingga ke benua lain. Kalo anda pernah dengar istilah "Demam Emas", itulah saat dimana para perantau Cina menyerbu pertambangan-pertambangan di Amerika. Di Nusantara persebaran perantau Cina makin masif di Jawa, Kalimantan, Sumatra dll. "Nan Yang" alias Asia Tenggara menjadi ladang yang menjanjikan keselamatan mereka dari runtuhnya negara Cina.
Perantau ini tak semuanya punya skill. Mereka bekerja sebagai buruh-buruh kasar, bersaing dengan para inlander. Pemerintah kolonial Belanda cukup terbuka menerima para pekerja Cina ini. Mereka dikenal mau dibayar murah namun rajin bekerja. Ya, mungkin sebagai orang asing yang tak paham budaya setempat, dihimpit tekanan hidup karena lari cari selamat, bisa dimaklumi kalau mereka tak ada pilihan lain selain menjadi mesin pekerja yang tangguh. Reputasi pekerja keras ini menjadi tradisi yang langgeng hingga saat ini.
Perlahan namun pasti, mereka berhasil membangun kekuatan ekonomi mereka. taraf hidup meningkat. Tak lagi jadi buruh namun meningkat jadi pedagang dan pengusaha. Sebelumnya tentu saja sudah banyak Cina pedagang, terutama keturunan yang sudah masuk ke sini sebelum prahara dinasti Qing. Kesuksesan ini lantas menjadi kesenjangan antara mereka dengan yang asli pribumi. Ritme hidup orang Jawa yang tak terlalu ambisius, santai, mengalir segera didahului oleh orang-orang keturunan yang sukses menjadi kaya. Ini gejala yang luas. Anda pun bisa amati hal serupa terjadi di lain latar sosial dan etnis.
Teman saya yang merantau di papua pernah cerita. Di Papua, warga suku asli sana akan iri pada kesuksesan pendatang yang lebih rajin. Serajin-rajinnya penduduk asli, pendatang akan lebih rajin.
Sama-sama terasing dari tanah leluhur, warga peranakan membangun persaudaraan yang kuat. Kalau dulu tujuan merantau mereka hanyalah cari makan dan selamat dari kekacauan kampung halaman, kini mereka punya tujuan jangka panjang. Mereka ingin hidup sukses. Sebagai pendatang atau keturunannya, tak mudah bagi mereka berbaur dengan warga asli yang diam-diam menyimpan kecemburuan. Maka mereka merasa lebih aman hidup dalam komunitas eksklusif. Makanya kemudian ada pecinan atau deretan ruko (rumah sekaligus toko) yang identik dengan tempat tinggal keturunan Cina.
Gelombang imigrasi baru merebak di pertengahan abad 19 saat Dinasti Qing sedang bobrok-bobroknya. Korupsi gila-gilaan para pejabat kerajaan membuat masyarakat tambah miskin. Makin parah lagi ketika Cina jatuh di tangan komunis dan Cina terpecah jadi Republik Rakyat Cina (dengan pemimpinnya Mao Zedong) dan Taiwan (dipimpin Sun Yat Sen). Dari pergolakan dalam negeri inilah, orang-orang terpaksa mencari penghidupan hingga ke benua lain. Kalo anda pernah dengar istilah "Demam Emas", itulah saat dimana para perantau Cina menyerbu pertambangan-pertambangan di Amerika. Di Nusantara persebaran perantau Cina makin masif di Jawa, Kalimantan, Sumatra dll. "Nan Yang" alias Asia Tenggara menjadi ladang yang menjanjikan keselamatan mereka dari runtuhnya negara Cina.
Perantau ini tak semuanya punya skill. Mereka bekerja sebagai buruh-buruh kasar, bersaing dengan para inlander. Pemerintah kolonial Belanda cukup terbuka menerima para pekerja Cina ini. Mereka dikenal mau dibayar murah namun rajin bekerja. Ya, mungkin sebagai orang asing yang tak paham budaya setempat, dihimpit tekanan hidup karena lari cari selamat, bisa dimaklumi kalau mereka tak ada pilihan lain selain menjadi mesin pekerja yang tangguh. Reputasi pekerja keras ini menjadi tradisi yang langgeng hingga saat ini.
Perlahan namun pasti, mereka berhasil membangun kekuatan ekonomi mereka. taraf hidup meningkat. Tak lagi jadi buruh namun meningkat jadi pedagang dan pengusaha. Sebelumnya tentu saja sudah banyak Cina pedagang, terutama keturunan yang sudah masuk ke sini sebelum prahara dinasti Qing. Kesuksesan ini lantas menjadi kesenjangan antara mereka dengan yang asli pribumi. Ritme hidup orang Jawa yang tak terlalu ambisius, santai, mengalir segera didahului oleh orang-orang keturunan yang sukses menjadi kaya. Ini gejala yang luas. Anda pun bisa amati hal serupa terjadi di lain latar sosial dan etnis.
Teman saya yang merantau di papua pernah cerita. Di Papua, warga suku asli sana akan iri pada kesuksesan pendatang yang lebih rajin. Serajin-rajinnya penduduk asli, pendatang akan lebih rajin.
Sama-sama terasing dari tanah leluhur, warga peranakan membangun persaudaraan yang kuat. Kalau dulu tujuan merantau mereka hanyalah cari makan dan selamat dari kekacauan kampung halaman, kini mereka punya tujuan jangka panjang. Mereka ingin hidup sukses. Sebagai pendatang atau keturunannya, tak mudah bagi mereka berbaur dengan warga asli yang diam-diam menyimpan kecemburuan. Maka mereka merasa lebih aman hidup dalam komunitas eksklusif. Makanya kemudian ada pecinan atau deretan ruko (rumah sekaligus toko) yang identik dengan tempat tinggal keturunan Cina.
SEKILAS KONDISI SOSIAL WARGA KETURUNAN CINA
Eksklusivitas mereka ini bukan tanpa latar belakang. Sepanjang sejarah mereka trauma dengan konflik. Kecemburuan sosial, diskriminasi dan lain-lain. Nusantara punya sejarah lumayan panjang soal kerusuhan rasial dengan keturunan Cina. Misalnya di Batavia pada tahun 1740. Hal ini memupuk sifat pragmatik mereka secara komunal: yakni main aman. Makanya mereka ke depannya lebih fokus di bidang non-politik. Tapi jelas salah besar jika dikatakan kaum peranakan Cina samasekali tidak peduli terhadap bangsa ini. Banyak tokoh cendekia yang merupakan warga keturunan Cina. Bahkan ikon demonstran muda yang kita kenal saat ini So Hok Gie, jelas-jelas keturunan Cina. Ada juga yang berkarir di bidang militer, misalnya Laksamana Muda TNI (Purn.) John Lie Tjeng Tjoan, salah satu pahlawan nasional.
Mengapa ketidaksukaan (untuk agak menghaluskan istilah kebencian) pada warga keturunan seakan merupakan hal terpendam bak "sekam yang terbakar"? Ini pun ada latar belakang yang kompleks.
Sejarah mencatat bahwa Belanda cenderung mengistimewakan warga peranakan dibanding inlander. Ini bagian dari politik pelemahan. Mungkin karena warga keturunan dinilai tak akan cukup setia pada tanah jajahan dan akan minim potensi memberontak. Tapi tentu saja sikap Belanda tidak selalu efektif. Kenyatannya terjadi peristiwa Geger Pacinan yang berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Dalam peristiwa itu Belanda secara represif menghabisi banyak warga keturunan yang memberontak gara-gara masalah ketakadilan. Pada masa geger itu terjadi, populasi peranakan Cina memang sedang tinggi-tingginya. Pemerintah Hindia Belanda seakan buntu akal dan melakukan pogrom secara sistematis.
Membludaknya populasi ini juga menjadi masalah di kemudian hari. Terlebih dengan status ekonomi mereka yang juga meningkat. Di masa Presiden Sukarno pembatasan aktivitas ekonomi warga keturunan tegas dilakukan. PP No. 10/1959 mengatur bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 desember 1959.
Tak cuma berusaha, mereka juga tak boleh beli tanah di desa atau kabupaten. Peraturan ini sempat menimbulkan kekisruhan setelah jatuh korban. Pemerintah Cina melakukan tekanan pada rezim Sukarno namun tak berhasil. Pada masa ini banyak warga keturunan ditarik pulang atau mengungsi ke Cina daratan. Masalahnya tak semua korban kebijakan itu memang warga asing (berstatus kewarganegaraan Cina). Sebagian mereka sudah menjadi warga yang terputus ikatan dengan budaya asal moyangnya. Mereka sudah tak ngerti bahasa Cina dan sehari-hari lebih banyak bicara bahasa lokal. Anda tak perlu heran, bahasa "kromo inggil"nya orang keturunan Cina di Surakarta itu bisa sangat josss dibanding yang Jawa asli hehehe (apalagi untuk ukuran remaja Jawa Timur yang memang tak terlalu mahir ber-kromo inggil)
Imbas dari kebijakan Sukarno membuat habitat warga keturunan terlokalisir di jalan-jalan utama. Inilah kenapa kita lebih banyak menemukan warga keturunan menempati kota-kota besar (juga sebagian kota kecil) di jalur-jalur ramai perniagaan. Maka di sini muncul stereotype "Cina toko". Di kota kecil, keturunan Cina kalau nggak buka toko ya jadi dokter.
Pada era orde baru, diskriminasi semakin tebal lagi. Warga keturunan katut kecipratan "dosa" gara-gara beberapa dari kaum mereka bermain politik dan berada di kubu PKI. Akibatnya status sosial warga keturunan makin tersudut. Kombinasi stigma "Cina, komunis dan PKI" adalah keburukan yang terendah di Indonesia. Yang menanggung itu semua, tak lain dan tak bukan tentu saja "gebyah uyah" semua warga keturunan yang nggak ikut-ikutan.
Selain ada label khusus pada KTP-nya, warga keturunan mendapat banyak pembatasan sosial budaya. Antara lain:
Mengapa ketidaksukaan (untuk agak menghaluskan istilah kebencian) pada warga keturunan seakan merupakan hal terpendam bak "sekam yang terbakar"? Ini pun ada latar belakang yang kompleks.
Sejarah mencatat bahwa Belanda cenderung mengistimewakan warga peranakan dibanding inlander. Ini bagian dari politik pelemahan. Mungkin karena warga keturunan dinilai tak akan cukup setia pada tanah jajahan dan akan minim potensi memberontak. Tapi tentu saja sikap Belanda tidak selalu efektif. Kenyatannya terjadi peristiwa Geger Pacinan yang berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Dalam peristiwa itu Belanda secara represif menghabisi banyak warga keturunan yang memberontak gara-gara masalah ketakadilan. Pada masa geger itu terjadi, populasi peranakan Cina memang sedang tinggi-tingginya. Pemerintah Hindia Belanda seakan buntu akal dan melakukan pogrom secara sistematis.
Membludaknya populasi ini juga menjadi masalah di kemudian hari. Terlebih dengan status ekonomi mereka yang juga meningkat. Di masa Presiden Sukarno pembatasan aktivitas ekonomi warga keturunan tegas dilakukan. PP No. 10/1959 mengatur bahwa semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin lagi setelah 31 desember 1959.
Tak cuma berusaha, mereka juga tak boleh beli tanah di desa atau kabupaten. Peraturan ini sempat menimbulkan kekisruhan setelah jatuh korban. Pemerintah Cina melakukan tekanan pada rezim Sukarno namun tak berhasil. Pada masa ini banyak warga keturunan ditarik pulang atau mengungsi ke Cina daratan. Masalahnya tak semua korban kebijakan itu memang warga asing (berstatus kewarganegaraan Cina). Sebagian mereka sudah menjadi warga yang terputus ikatan dengan budaya asal moyangnya. Mereka sudah tak ngerti bahasa Cina dan sehari-hari lebih banyak bicara bahasa lokal. Anda tak perlu heran, bahasa "kromo inggil"nya orang keturunan Cina di Surakarta itu bisa sangat josss dibanding yang Jawa asli hehehe (apalagi untuk ukuran remaja Jawa Timur yang memang tak terlalu mahir ber-kromo inggil)
Imbas dari kebijakan Sukarno membuat habitat warga keturunan terlokalisir di jalan-jalan utama. Inilah kenapa kita lebih banyak menemukan warga keturunan menempati kota-kota besar (juga sebagian kota kecil) di jalur-jalur ramai perniagaan. Maka di sini muncul stereotype "Cina toko". Di kota kecil, keturunan Cina kalau nggak buka toko ya jadi dokter.
Pada era orde baru, diskriminasi semakin tebal lagi. Warga keturunan katut kecipratan "dosa" gara-gara beberapa dari kaum mereka bermain politik dan berada di kubu PKI. Akibatnya status sosial warga keturunan makin tersudut. Kombinasi stigma "Cina, komunis dan PKI" adalah keburukan yang terendah di Indonesia. Yang menanggung itu semua, tak lain dan tak bukan tentu saja "gebyah uyah" semua warga keturunan yang nggak ikut-ikutan.
Selain ada label khusus pada KTP-nya, warga keturunan mendapat banyak pembatasan sosial budaya. Antara lain:
- Keharusan mengganti nama dengan nama-nama bau lokal. Meski sudah ganti, setidaknya jejak "asing" ini masih bisa kita kenali. Simak saja nama-nama yang khas warga keturunan: Tanuwijaya, Wongso, Tanoto, Lianto, Chandra dll.
- Melarang segala bentuk penerbitan yang berbahasa serta beraksara Cina.
- Membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan hanya dalam lingkup terbatas (keluarga).
- Melarang perayaan hari raya tradisional Tionghoa di muka umum.
- Melarang keberadaan sekolah-sekolah khusus Tionghoa.
PAGAR TINGGI ADA BELINGNYA, DIUNDANG KERJA BAKTI GAK MAU
Tipikal asosial, eksklusif sangat sering direkatkan pada warga peranakan Cina. Rumah yang "gedongan", pagarnya tinggi-tinggi dan dikasih beling memang nyata saya temui. Namun setidaknya lewat pengalaman saya, upaya untuk bersosialisasi masih terus diupayakan meski sukar untuk menghapus kesan eksklusivitas itu.
Misalnya keluarga kami, terutama ibu dan bapak sudah lama menjalin keakraban dengan warga keturunan untuk urusan tak hanya bisnis. Sampai sekarang hubungan itu juga masih menurun ke anak-anaknya. Nyonya pemilik toko yang partneran sama ibu saya itu cukup sering kirim masakan bikinan rumah buat mbakyu saya. Saya pribadi juga pernah diajak makan bareng keluarga keturunan setelah saya bantu rekan kerja mereka yang orang Taiwan. Jarang-jarang lho saya bisa ngalamin itu hehe.
Ada juga anomali yang cukup unik. Kejadiannya masih di kampung saya, Wlingi. Ada warga keturunan Cina ikut kerja bakti hehehe. Unik nggak sih? Itu terjadi tahun 90an jaman saya SD. Ada satu warga keturunan ikutan pegang linggis bangun poskamling.
Ya memang kalo disuruh ikutan kerjabakti rata-rata mereka akan pilih donasi. Ada bagusnya, ada enggaknya. Bagusnya ya ada dana nyata ... rata-rata orang kita kan paling susah keluar duit. Jeleknya ya mereka makin alienated ... tanggungjawab sosial kan tak seluruhnya bisa dimanifestasikan dalam bentuk sumbangan. Orang juga perlu kedekatan emosional. Apalagi dengan orang berciri fisik beda dengan yang pribumi. Tapi soal pribumi, asli nggak asli itu adalah hal serius lain yang perlu kita bahas secara terpisah.
Jadi eksklusivitas warga keturunan adalah produk dinamika sosial yang sangat kompleks. Musti dirunut jauh hingga ke sebelum abad 19. Para aktivis sosial budaya mustinya perlu membuat strategi kebudayaan yang memungkinan antar etnik ini berbaur secara nyaman dan aman. Karena sejauh ini katarsis pembauran sosial yang efektif cuma satu ... AGAMA.
Perlu saya sempatkan menyinggung bahwa interaksi Islam dan keturunan Cina itu penting dalam proses sosial. Alasannya satu: agama adalah hal yang paling efektif untuk menciptakan pembauran. Apalagi Islam sebagai agama mayoritas.
Tapi kan ya nggak bisa memaksa warga keturunan agar bisa memeluk Islam kan?
Relasi Cina dan Islam sesungguhnya sudah sangat tua. Penyebar Islam di Nusantara pun sebagian juga pedagang-pedagang Cina Muslim. Warga keturunan kalo beragama Islam konon bisa "ilang ke-Cinaannya" hehe. Selama masih ngikut ritual dan tradisi Islam pastinya sukar untuk eksklusif. Tapi jangan lantas jadi fasis dengan teriak "Islamkan orang-orang Cina" lho ya.
Yang saya amati di kampung saya sendiri, upaya berbaur terus dilakukan oleh dua pihak yang warga asli dengan warga keturunan. Misalnya saling mengunjungi saat hari raya. Tahun kemarin pas Imlek, mbakyu saya juga mengunjungi rekan Tionghoanya. Sebaliknya juga saat lebaran mereka mengucapkan selamat.
Misalnya keluarga kami, terutama ibu dan bapak sudah lama menjalin keakraban dengan warga keturunan untuk urusan tak hanya bisnis. Sampai sekarang hubungan itu juga masih menurun ke anak-anaknya. Nyonya pemilik toko yang partneran sama ibu saya itu cukup sering kirim masakan bikinan rumah buat mbakyu saya. Saya pribadi juga pernah diajak makan bareng keluarga keturunan setelah saya bantu rekan kerja mereka yang orang Taiwan. Jarang-jarang lho saya bisa ngalamin itu hehe.
Ada juga anomali yang cukup unik. Kejadiannya masih di kampung saya, Wlingi. Ada warga keturunan Cina ikut kerja bakti hehehe. Unik nggak sih? Itu terjadi tahun 90an jaman saya SD. Ada satu warga keturunan ikutan pegang linggis bangun poskamling.
Ya memang kalo disuruh ikutan kerjabakti rata-rata mereka akan pilih donasi. Ada bagusnya, ada enggaknya. Bagusnya ya ada dana nyata ... rata-rata orang kita kan paling susah keluar duit. Jeleknya ya mereka makin alienated ... tanggungjawab sosial kan tak seluruhnya bisa dimanifestasikan dalam bentuk sumbangan. Orang juga perlu kedekatan emosional. Apalagi dengan orang berciri fisik beda dengan yang pribumi. Tapi soal pribumi, asli nggak asli itu adalah hal serius lain yang perlu kita bahas secara terpisah.
Jadi eksklusivitas warga keturunan adalah produk dinamika sosial yang sangat kompleks. Musti dirunut jauh hingga ke sebelum abad 19. Para aktivis sosial budaya mustinya perlu membuat strategi kebudayaan yang memungkinan antar etnik ini berbaur secara nyaman dan aman. Karena sejauh ini katarsis pembauran sosial yang efektif cuma satu ... AGAMA.
Perlu saya sempatkan menyinggung bahwa interaksi Islam dan keturunan Cina itu penting dalam proses sosial. Alasannya satu: agama adalah hal yang paling efektif untuk menciptakan pembauran. Apalagi Islam sebagai agama mayoritas.
Tapi kan ya nggak bisa memaksa warga keturunan agar bisa memeluk Islam kan?
Relasi Cina dan Islam sesungguhnya sudah sangat tua. Penyebar Islam di Nusantara pun sebagian juga pedagang-pedagang Cina Muslim. Warga keturunan kalo beragama Islam konon bisa "ilang ke-Cinaannya" hehe. Selama masih ngikut ritual dan tradisi Islam pastinya sukar untuk eksklusif. Tapi jangan lantas jadi fasis dengan teriak "Islamkan orang-orang Cina" lho ya.
Yang saya amati di kampung saya sendiri, upaya berbaur terus dilakukan oleh dua pihak yang warga asli dengan warga keturunan. Misalnya saling mengunjungi saat hari raya. Tahun kemarin pas Imlek, mbakyu saya juga mengunjungi rekan Tionghoanya. Sebaliknya juga saat lebaran mereka mengucapkan selamat.
KECEMASAN DAN KECEMBURUAN YANG LATENT
Now the "curhat" part ... you may stop reading here. Boleh berhenti baca dari sini. Wong setelah ini saya cuma mo curhat.
Dikotomi "warga asli/pribumi VS warga keturunan/pernakan" adalah istilah yang ujungnya bermasalah. Mereka ini sudah hidup ratusan tahun di sini, makan dan kerja di sini, sudah putus ikatan dengan negara mbah moyangnya. Sedangkan kita juga kebanyakan nggak asli-asli amat keturunan homo wajakensis. Jadi validkah sebutan "non pribumi"?
Bagi rekan-rekan yang diam-diam rasialis itu saya juga coba pahami latarnya sih. Mungkin mereka pernah punya masalah sama oknum keturunan Cina yang busuk. Mungkin pernah ditipu soal bisnis atau semacamnya. Wajar. Kita punya kecemburuan kolektif dan latent soal warga keturunan sebagai "alien" yang lebih sukses. Itu membuat kita lebih mudah melakukan stigmatisasi.
Seorang seniman pesohor yang saya kenal bahkan pernah berucap di hadapan saya (off the record), "kalo ada pengganyangan Cina saya bakal ikut deh." Dia pernah punya pengalaman buruk soal kerjasama warga keturunan ... mantan bosnya kalo gak salah.
Mereka yang busuk itu pastinya juga satu kotak sama "pribumi" yang busuk. Hanya karena ketegangan antar ras yang terus-terusan terpeliharalah kita melihatnya sebagai ancaman.
Kita masih ingat kepanikan netizen saat ada kabar ribuan pekerja Cina menyerbu Indonesia. Terpupuk sentimen rasial yang latent, kita menjadi waswas akan bahaya penjajahan Cina ... sementara gawai yang kita pakai juga masih ... made in China. Di lapisan politik kecemasan ini juga terus dipupuk. Anehnya beberapa orang keturunanpun malah bermain api dengan hal ini.
Setelah tokoh fenomenal Ahok dipenjara, ketegangan baru kini dimulai. Kaum pro nasionalis dihadapkan pada kaum pro relijius. Lagi-lagi minoritas keturunan menjadi arah kecemasan ... bagaimana jika mereka menguasai Indonesia? Makin absurd lagi karena beberapa bermain api politik, menguasai media dan bahkan memainkan peran orang-orang berpaham radikal.
Akankah pelajaran penting dari tragedi 1965 dan 1998 masih sanggup menjaga kewarasan kita?
Saya mengamati betapa banyak orang yang saya pikir bisa bijak bersikap, malah turut menyebar hoax, meme kebencian rasial, memanas-manasi situasi...dan mereka kayak gak merasa ada yang salah. Saya pribadi kehabisan akal untuk bagaimana menyikapi ketegangan ini selain melampiaskannya dalam karya-karya hiburan semacam komik saru "Timun Mas" (damn...)
Mungkin saya terlalu berlebihan jika ngomong bahwa Indonesia adalah bangsa yang masih balita untuk urusan literasi dan kedewasaan sosial. Tetapi apa yang tersaji di depan saya... rasanya susah menilainya selain itu.
Akhir kata saya cuma bisa curhat ... omong-omong makasih bagi yang udah baca curhat saya sampai di paragraf ini. Awalnya kayak essai ilmiah lha kok ujungnya jadi curhat. Anda pasti mau misuh, "Juancuuuuukk!" hahaha
Dunia ini cuma satu. Mau tak mau kita harus berbagi ruang. Tapi saya juga tahu ... berbagi kan bukan watak dasar manusia bumi ya?
Salam Bhineka Tunggal Ika. Satu Bangsa Satu Raisa eh maksud saya Rasa.
======
Dikotomi "warga asli/pribumi VS warga keturunan/pernakan" adalah istilah yang ujungnya bermasalah. Mereka ini sudah hidup ratusan tahun di sini, makan dan kerja di sini, sudah putus ikatan dengan negara mbah moyangnya. Sedangkan kita juga kebanyakan nggak asli-asli amat keturunan homo wajakensis. Jadi validkah sebutan "non pribumi"?
Bagi rekan-rekan yang diam-diam rasialis itu saya juga coba pahami latarnya sih. Mungkin mereka pernah punya masalah sama oknum keturunan Cina yang busuk. Mungkin pernah ditipu soal bisnis atau semacamnya. Wajar. Kita punya kecemburuan kolektif dan latent soal warga keturunan sebagai "alien" yang lebih sukses. Itu membuat kita lebih mudah melakukan stigmatisasi.
Seorang seniman pesohor yang saya kenal bahkan pernah berucap di hadapan saya (off the record), "kalo ada pengganyangan Cina saya bakal ikut deh." Dia pernah punya pengalaman buruk soal kerjasama warga keturunan ... mantan bosnya kalo gak salah.
Mereka yang busuk itu pastinya juga satu kotak sama "pribumi" yang busuk. Hanya karena ketegangan antar ras yang terus-terusan terpeliharalah kita melihatnya sebagai ancaman.
Kita masih ingat kepanikan netizen saat ada kabar ribuan pekerja Cina menyerbu Indonesia. Terpupuk sentimen rasial yang latent, kita menjadi waswas akan bahaya penjajahan Cina ... sementara gawai yang kita pakai juga masih ... made in China. Di lapisan politik kecemasan ini juga terus dipupuk. Anehnya beberapa orang keturunanpun malah bermain api dengan hal ini.
Setelah tokoh fenomenal Ahok dipenjara, ketegangan baru kini dimulai. Kaum pro nasionalis dihadapkan pada kaum pro relijius. Lagi-lagi minoritas keturunan menjadi arah kecemasan ... bagaimana jika mereka menguasai Indonesia? Makin absurd lagi karena beberapa bermain api politik, menguasai media dan bahkan memainkan peran orang-orang berpaham radikal.
Akankah pelajaran penting dari tragedi 1965 dan 1998 masih sanggup menjaga kewarasan kita?
Saya mengamati betapa banyak orang yang saya pikir bisa bijak bersikap, malah turut menyebar hoax, meme kebencian rasial, memanas-manasi situasi...dan mereka kayak gak merasa ada yang salah. Saya pribadi kehabisan akal untuk bagaimana menyikapi ketegangan ini selain melampiaskannya dalam karya-karya hiburan semacam komik saru "Timun Mas" (damn...)
Mungkin saya terlalu berlebihan jika ngomong bahwa Indonesia adalah bangsa yang masih balita untuk urusan literasi dan kedewasaan sosial. Tetapi apa yang tersaji di depan saya... rasanya susah menilainya selain itu.
Akhir kata saya cuma bisa curhat ... omong-omong makasih bagi yang udah baca curhat saya sampai di paragraf ini. Awalnya kayak essai ilmiah lha kok ujungnya jadi curhat. Anda pasti mau misuh, "Juancuuuuukk!" hahaha
Dunia ini cuma satu. Mau tak mau kita harus berbagi ruang. Tapi saya juga tahu ... berbagi kan bukan watak dasar manusia bumi ya?
Salam Bhineka Tunggal Ika. Satu Bangsa Satu Raisa eh maksud saya Rasa.
======
Penulis: Gugun, orang Jawa berdarah campuran ... campur kegelisahan